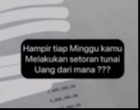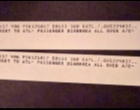Glorifikasi Gangguan Mental Akibat 'Joker', Maraknya Klaim Gangguan Mental Hanya Bermodal Self-Diagnosis yang Justru Berbahaya

IDWS, Jumat, 11 Oktober 2019 - Booming film Joker yang dibintangi Joaquin Phoenix membuat aparat berwajib di Amerika Serikat (AS) siap siaga menjaga bioskop-bioskop di sana. Semua itu terjadi karena ketakutan terulangnya penembakan massal saat penayangan The Dark Knight Rises di Cinema 16, Colorado, tahun 2012 silam.
Di era modern ini, masalah kesehatan mental memang telah lama menjadi momok menakutkan, terutama bagi generasi muda. Akan tetapi tingkat kepedulian serta perilaku prejudice membuat orang-orang depresi cenderung menolak berinteraksi dengan masyarakat, bahkan memilih mengakhiri hidup mereka sendiri atau hidup orang lain yang tak bersalah.

Joker mengisahkan tentang Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) yang mengalami gangguan mental dan depresi hingga membuatnya menjadi kriminal dengan julukan Joker. (Warner Bros. Pictures)
Film Joker terbaru kali ini membuat kepedulian akan kesehatan mental makin meningkat berkat arahan brilian dari Todd Phillips serta dedikasi akting luar biasa dari Joaquin Phoenix. Namun bak dua sisi uang logam, di saat film tersebut membuat kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, di sisi lain timbul fenomena glorifikasi gangguan mental sebagai sesuatu yang keren.
Glorifikasi gangguan mental serta menggunakan gangguan mental sebagai sarana untuk membenarkan keburukan pribadi diri sendiri
Di internet, demi meningkatkan traffic suatu situs atau laman media sosial, pihak-pihak non-profesional di bidang psikologi maupun gangguan mental, membuat artikel yang utamanya menjabarkan ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental atau depresi tanpa pengetahuan yang mencukupi.
Padahal dibutuhkan ilmu serta pengetahuan yang tak sedikit untuk menjabarkan hal yang sangat dalam dan luas seperti gangguan mental.
Mendiagnosa masalah gangguan mental tidak mudah karena diperlukan keahlian khusus dan pengetahuan mengenai diagnosis masalah, gangguan, atau sindrom mental. Ada juga obat-obatan yang dikhususkan bagi penderita gangguan mental dan depresi, yang tidak bisa sembarangan diminum begitu saja karena harus sesuai anjuran tenaga ahli. Jadi tidak asal konsumsi saja.
Dengan booming-nya film Joker yang memang menitikberatkan akan gangguan mental dan depresi, yang melahirkan sosok kriminal Joker. Film garapan Todd Phillips ini memicu semakin banyaknya orang-orang yang mengaku mengalami gangguan mental atau depresi. Parahnya lagi, kebanyakan dari mereka justru mengagungkan (glorifikasi) gangguan mental dan malah bangga bila disebut menderita gangguan mental.

Banyak sekali generasi muda yang seringkali memamerkan hasil-hasil "tes gangguan mental" mereka di internet, seperti berlomba-lomba membuktikan siapa yang lebih parah gangguan mentalnya. (Warner Bros. Pictures)
Padahal mereka cuma melakukan self-diagnosis dari internet, yang hampir bisa dipastikan hasilnya tidak benar atau tidak akurat sama sekali, menimbulkan kesalahan persepsi dan membuat orang-orang yang sebenarnya tidak mengalami gangguan mental malah menyalahkan gangguan mental atas kelemahan mereka sendiri.
Misalnya ada orang yang curiga dirinya mengalami gangguan mental karena merasa dimusuhi oleh semua orang. Ia lalu melakukan self-diagnosis di internet dan hasilnya ia mengalami depresi. Padahal sebenarnya, memang dia itu toxic sehingga membuat teman-temannya menghindarinya.
Namun ia tidak mau mengakui ke-toxic-an dirinya sendiri dan menggunakan gangguan mental atau depresi sebagai pembenaran perilaku toxic-nya. Orang seperti ini, tidak jauh beda dengan self-denial.
Self-diagnosis atau self-destruct?
Salah satu wujud self-diagnosis yang marak di dunia maya adalah "tes kesehatan mental" di berbagai media sosial atau situs-tisut di internet. Sayangnya, orang-orang — terutama generasi muda, dengan mudahnya memercaya hasil dari tes-tes tersebut, yang biasanya hanya terdiri dari beragam pertanyaan saja. Sudah begitu, semakin "parah" hasil tes kesehatan mereka, malah semakin bangga orang-orang memamerkan hasil tersebut ke akun media sosial masing-masing.

Self-diagonsis gangguan mental di internet tak jauh beda dengan berharap bisa menemukan obat kanker lewat googling. (Google.com)
Padahal self-diagnosis seperti itu sangat berbahaya karena kesimpulan yang didapat terkait kesehatan mental seseorang belum tentu tepat, sehingga penanganan yang diambil pun salah kaprah pula. Bahkan tak menutup kemungkinan orang-orang yang self-diagnosis ini merusak tubuh mereka sendiri karena meminum obat penenang tanpa anjuran dokter, atau mengonsumsi narkoba.
Melansir theconvertion.com, ada pasien yang mendiagnosis diri sendiri mengalami depresi, lalu kecanduan obat penenang. Padahal menurut pemeriksaan ahli profesional, pasien itu hanya memiliki "serangan panik" yang bisa ditangani dengan terapi psikologis dalam satu-dua bulan. Akibat mengonsumsi obat penenang tanpa anjuran ahli profesional, sang pasien terpaksa ditangani secara medis dan psikolis selama 6-12 bulan. Biayanya menjadi berlipat ganda, belum lagi dampak emosional serta membuang waktu percuma.
Bahkan para ahli profesional di bidang gangguan mental dan depresi pun tak berani melakukan diagnosis pada diri mereka sendiri. Mereka juga meminta tolong atau berkonsultasi dengan sesama rekan profesional di bidangnya untuk memastikan penanganan apa yang tepat.
Kalau sudah begitu, bukannya berarti self-diagnosis sama saja dengan self-destruct (menghancurkan diri sendiri)?
Gangguan mental dan depresi sangat tidak menyenangkan. It's ugly and bothersome.
Penulis sendiri heran "kok ada orang bisa bangga mengalami gangguan mental?" Kalian tidak perlu malu bila memang mengidap gangguan mental atau depresi, namun di saat yang sama, gangguan mental bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan dan digunakan untuk memanipulasi orang lain, bahkan membohongi diri sendiri.
Think carefully, mental illness is not a joke, and it's not something to be proud of. No one should be proud for being mentally ill.
(Stefanus/IDWS)